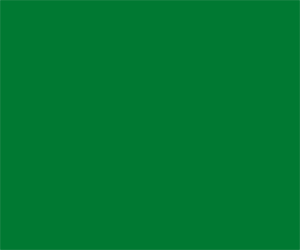Lembaga pegiat antikorupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat rata-rata vonis hakim dalam kasus korupsi sepanjang 2016 hanya 26 bulan penjara.
Peneliti Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Aradila Caesar mengatakan angka tersebut diperoleh berdasarkan hasil pemantauan terhadap 573 putusan kasus korupsi yang dikeluarkan pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, dan Mahkamah Agung.
“Rata-rata vonis untuk koruptor selama tahun 2016 adalah 26 bulan, vonis ini kurang lebih hanya 1/8 dari hukuman maksimal,” kata Aradila dalam sebuah diskusi di kantor ICW, Jakarta.
Menurutnya, vonis ringan dalam kasus korupsi paling sering dikeluarkan oleh pengadilan tingkat pertama. Dari 420 putusan yang dikeluarkan untuk 467 terdakwa, sebanyak 354 terdakwa dijatuhkan vonis di bawah empat tahun penjara.
Kemudian disusul pengadilan tingkat banding, yang memutuskan 80 dari 133 terdakwa mendapatkan vonis penjara di bawah empat tahun, serta Mahkamah Agung yang menjatuhkan vonis di bawah empat tahun penjara bagi 14 dari 32 terdakwa perkara korupsi.
“Pengadilan tingkat pertama, dari 420 putusan rata-rata vonis satu tahun 11 bulan, pengadilan tingkat banding dari 121 putusan rata-rata vonis dua tahun enam bulan, sedangkan Mahkamah Agung dari 32 putusan rata-rata vonis empat tahun satu bulan,” katanya.
Kecenderungan tiga tingkat pengadilan menjatuhkan vonis ringan dalam perkara korupsi perlu dievaluasi. Aradila mengatakan, pengadilan tindak pidana korupsi harusnya berkaca pada semangat Pengadilan Tinggi Militer II Jakarta yang menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap Brigadir Jenderal Teddy Hernayadi.
Teddy terbukti bersalah pada perkara korupsi pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) sebesar US$12,4 juta saat menjabat Kepala Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Kementerian Pertahanan periode 2010-2014 dengan pangkat Kolonel.
“Vonis untuk koruptor tidak memberikan efek jera, karena pengadilan masih memberikan hukuman yang ringan. Ini bukan pertama kali terjadi, tapi terus berulang sejak 2013,” ujar Aradila.
Peneliti Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW lainnya, Tama S Langkun, mengatakan, ringannya vonis terhadap koruptor ini tidak dapat dilepaskan dari tuntutan jaksa. Jaksa dinilai gagal dalam memformulasikan hukuman yang tepat bagi terdakwa.
Jaksa, lanjutnya, cenderung menuntut terdakwa secara ringan, tanpa disertai kewajiban uang pengganti, pencabutan hak politik, serta penggunaan pasal tindak pidana pencucian uang.
“Jaksa seolah tidak memiliki keberpihakan terhadap pemberantasan korupsi,” kata Tama.
Ia menyayangkan butir ayat 4 Pasal 10 KUHP tentang denda pidana yang tak terimplementasi dengan maksimal. Catatan ICW di tahun lalu, 346 terdakwa dikenakan denda ringan dengan maksimal nominal Rp 50 juta.
“Di samping itu juga masih terdapat kemungkinan terdakwa tak membayar denda dan menggantinya dengan pidana kurungan yang relatif singkat. Padahal Undang-undang Tipikor Pasal 2 dan 3 menyebutkan denda pidana yang dapat dikenakan ke terdakwa,” katanya.
Disparitas Putusan
Selain vonis ringan, disparitas putusan juga masih menjadi persoalan yang serius dalam peradian kasus korupsi. Ia mempertanyakan, alasan hakim sama-sama menjatuhkan vonis satu tahun penjara dalam dua korupsi yang menyebabkan kerugian negara berbeda.
Tama mengambil contoh, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis Pegawai Negeri Sipil bernama Wiwit Ayu Wulandari yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp12,82 miliar rupiah pada 2015. Vonis penjara yang sama juga dikeluarkan Pengadilan Negeri Kupang terhadap pegawai swasta bernama Andi Sianto yang hanya menyebaban kerugian negara sebsar Rp14,38 juta.
“Ini patut dipertanyakan, mengapa? Apa ukurannya, pidana putusannya hanya satu tahun? Sayangnya pengadilan tak bisa menjelaskan hal ini,” katanya.
Dia melanjutkan, latar belakang terdakwa korupsi selama 3 tahun belakangan mayoritas adalah pegawai negeri sipil. Tahun lalu sebanyak 217 PNS terjerat pasal korupsi. Sementara objek yang masih menjadi primadona di mata para koruptor adalah pengadaan barang dan jasa.
“Jika berkaca pada aktor pelaku korupsi sepanjang 2013 sampai 2016, aktor dari kalangan PNS Pemkot, Pemkab, Pemprov adalah yang terbanyak. Dari 573 putusan kasus korupsi di 2016, hanya ada tujuh putusan yang memvonis terdakwa dengan pidana tambahan, pencabutan hak politik,” ungkap Tama.
Tama kemudian mencontohkan nasib Muhammad Sanusi yang merupakan terdakwa kasus suap Rapeda Reklamasi dan Damayanti Wisnu Putranti yang merupakan terdakwa kasus suap proyek pembangunan jalan Maluku. Menurut ICW, keduanya masih beruntung.
“Saat itu jaksa menuntut agar hakim mencabut hak politik keduanya, namun saat pembacaan putusan, hakim justru menolak tuntutan jaksa dengan berbagai alasan,” keluh Tama.
Terakhir, Tama nenyoroti pengelolaan informasi di Mahkamah Agung yang dinilai masih malas mengunggah putusan pengadilan tipikor, mengunggah salinan putusan yang tak dapat diunduh, mengunggah salinan putusan yang tak dapat dibaca, ringkasan putusan tidak detil, pilihan menu di website rumit.
“Reformasi di MA tidak berjalan optimal. Reformasi hanya dimaknai sekedar diuploadnya putusan-putusan pengadilan di website. Komitmen antikorupsi pimpinan MA minim,” kata Tama.