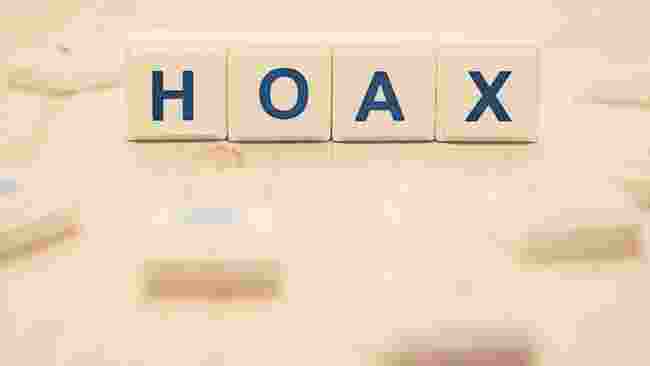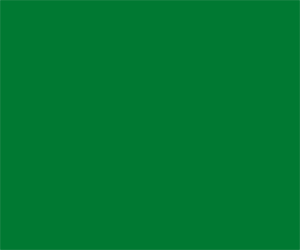Sebelum jadi presiden, Pak Jokowi adalah keturunan China (bernama Wie Jo-Koh), non-Muslim dan kader yang punya misi menghidupkan kembali komunisme di Indonesia. Setelah jadi presiden, orang tahu bahwa orangtuanya Jawa asli, tinggal di pinggir Solo, sudah naik haji sekeluarga, berkuasa dengan didukung PDI Perjuangan, bukan Partai Komunis China.
Apakah ada orang yang benar-benar percaya kalau pak Jokowi (gemar sarungan, alumni Fakultas Kehutanan UGM, bicara dengan aksen Jawa medok) adalah kader PKC yang jadi presiden demi kejayaan Tiongkok? Jawabnya mungkin tidak–minimal, sedikit yang betul-betul meyakini tuduhan seperti itu. Toh sampai sekarang, posting-an seperti itu tidak pernah betul-betul berhenti.
Dan memang itu lah salah satu karakter hoax, berita palsu, kabar bohong atau apa pun namanya: muncul bukan untuk membuat orang percaya. Yang signifikan dari hoax adalah kehadirannya untuk menciptakan keraguan sehingga orang bisa mempertanyakan hal yang sudah dibenarkan sebagai fakta umum sebelumnya. Orang tahu Pak Jokowi kecil tinggal di pinggiran Solo, raut muka dan tutur katanya menunjukkan identitas khas orang Jawa–eh, tapi apa yang bisa jamin dia bukan benar-benar keturunan China?
Tentu saja penyebutan Pak Jokowi dalam tulisan ini ilustrasi belaka. Pak SBY pernah jadi korban hoax, begitu juga Pak Prabowo dan Bu Mega, juga ratusan mungkin ribuan politisi lain. Tunggu sampai 2019 ketika pemilihan presiden akan berlangsung. Kalau Pak Jokowi Pak Prabowo Pak SBY atau Bu Mega nyalon lagi, dijamin berita palsu model lama dan baru akan trending kembali.
Kenapa begitu?
Satu, karena ada kebutuhan untuk menabur kembali bibit kabar bohong demi keuntungan politik. Dua, dan yang jadi poin tulisan ini, karena media sosial masih akan jadi salah satu rujukan utama informasi warga. Kecuali kalau ada terobosan teknologi yang mampu mengatasi problem hoax via medsos.
Sekarang ini terobosan itu belum ketemu. Sementara di Indonesia, menurut pencatat statistik We Are Social, pengguna medsos diperkirakan mencapai 87 juta tahun ini–78% nya memanfaatkan aplikasi jejaring Facebook. Lebih dari 66 juta orang mengakses medsos lewat ponsel mereka–total nomor ponsel aktif mencapai 326 juta.
Mencegah penyebaran hoax dengan skala penggunaan medsos semasif ini antara lain jadi persoalan Panitia Khusus DPR yang sedang menyiapkan Kodifikasi RUU Pemilu. Meski bisa dimanfaatkan untuk banyak kepentingan, Pansus khawatir hoax akan jadi masalah besar pada penyelenggaran pemilu.
Di negara dengan demokrasi semaju Amerika Serikat saja, kabar bodong dianggap sebagai salah satu unsur paling beracun dalam Pilpres 2016. Studi tim Universitas Stanford menyebut berita hoax yang dianggap merugikan pencalonan Hillary Clinton ‘dimakan’ pendukung Donald Trump dan menyebar 30 juta kali di medsos. Sebaliknya berita bohong tentang Trump dibagikan belasan juta kali oleh pendukung Clinton. Sirkulasi puluhan juta kali hoax ini diduga mempengaruhi hasil akhir sehingga Trump menang.
Banyak negara khawatir berita palsu merusak proses demokrasi karena sederhananya pola penyebaran. Dalam platform Facebook misalnya, sangat mudah menemukan kabar dengan tingkat kebenaran sumir di sisi kanan layar yang merupakan materi berbayar–baik iklan maupun berita.
Usulan mengenakan denda muncul dari pemikiran: karena fake news merupakan dampak teknologi yang diciptakan Facebook, maka pemilik teknologi yang mesti bertanggung jawab mengatasi. Sejenis logika ‘kau yang mulai kau yang mengakhiri.’
Partai Sosial Demokrat Jerman tahun lalu mengusulkan denda maksimal 500.000 euro (Rp7 miliar lebih) untuk tiap kabar bohong yang beredar di Facebook lebih dari 24 jam. Usulan itu akan dibahas di parlemen Jerman tahun ini.
Google juga sudah bertahun-tahun dianggap punya reputasi jelek membiarkan sirkulasi berita palsu dalam gudang datanya. Termasuk di antaranya, Google dianggap berperan menyebar kabar kebencian (hate speech) dengan algoritma yang dipakai pada mesin pencarinya. Kata kunci pencarian ‘Allahu Akbar’ misalnya, akan merujuk pada laman Wikipedia yang menjelaskan arti kata itu, diikuti tiga berita terkait teratas yang seluruhnya mengaitkan seruan takbir itu dengan aksi terorisme.
Bos Apple, Tim Cook, mengakui perusahaan teknologi mestinya bisa menciptakan alat penyaring hoax dan bukan cuma diam membiarkan komplain berdatangan bertubi-tubi. Setelah meraih asset sampai triliunan dollar dari ledakan pengguna medsos (termasuk dari peredaran berita setengah palsu dengan model click bait, raksasa teknologi tidak bisa pura-pura bego membiarkan aplikasinya jadi sumber kebohongan dan kebencian.
Desember lalu Facebook mengumumkan insiatif anti-hoax-nya yang di-posting langsung oleh sang juragan, Mark Zuckerberg. Bermitra dengan pihak ketiga (termasuk FactCheck.Org dan ABC News), Facebook mengklaim mengubah skema pelaporan berita palsu menjadi lebih mudah. Setelah dilaporkan, berita yang dicurigai palsu akan dicek dan bila tak lolos verifikasi akan diberi tanda khusus. Meski masih bisa di-share, pengguna akan diingatkan soal kesahihan berita tersebut sebelum membaginya dalam jaringan Facebook. Berita yang sudah diberi tanda tak bisa masuk kategori promosi maupun iklan.
Sayangnya, proses verifikasi ini bisa bermasalah. Bagimana kita tahu pihak ketiga yang jadi mitra Facebook berlaku lurus dan tak partisan–sebagian dari mitra ini adalah media dan lembaga yang mungkin punya kecondongan politik tertentu. Menyerahkan penyaringan berita pada mereka bisa berarti membiarkan sensor berita dan kebebasan berpendapat di platform Facebook. Alih-alih menyelesaikan persoalan hoax, proses ini bisa jadi membawa persoalan baru. Mirip Dewan Pers yang menetapkan barisan media dengan cap ‘terverifikasi’ dimana beberapa media justru dipertanyakan keabsahannya, sementara media yang selama ini relatif dipercaya publik malah tak muncul namanya.
Antara lain dengan menyitir alasan kebebasan atas sensor ini, berbeda dengan Facebook, Google memilih metode verifikasi di hulu: dengan mengenali hoax di sumber beritanya diharapkan peredarannya tak mengalir sampai jauh. Dua pekan lalu Google Indonesia mengundang wartawan dalam sebuah sesi pelatihan mengenali berita palsu dan menjadwalkan serangkain sesi serupa untuk berbagai media di Indonesia tahun ini.
Kalau berbagai metode verifikasi ini tak berhasil mencegah laju kabar palsu beredar, apa bisa Indonesia ikut menerapkan sanksi denda pada perusahaan-perusahaan teknologi?
Mereka boleh lega. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan pemerintah tak melihat denda sebagai solusi terhadap hoax. Rudiantara menilai model verifikasi dan kampanye anti-hoax lebih mungkin berhasil ketimbang model denda ganti rugi. Tentu saja, pemikirannya mungkin berubah.
Pertama, verifikasi baik oleh mitra Facebook maupun internal media bukan proses sederhana, bisa saja gagal sehingga hoax tetap merajalela. Kedua, kalau Jerman kelak sukses menetapkan denda maka sangat mungkin jadi preseden dan ditiru banyak negara lain di dunia–termasuk Indonesia.
Jadi patut dilihat apakah pemerintah akan berubah pendapat kalau perang hoax kembali bergolak pada arena Pilpres 2019 nanti.