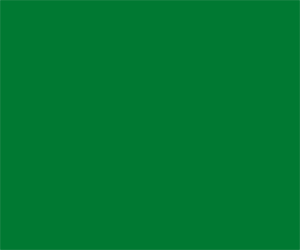Rencana pemerintah mengontrol kenaikan harga tanah dengan memungut pajak final progresif atas transaksi penjualan maupun dua skema pajak tanah lainnya menarik perhatian Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA).
CITA yang digawangi Yustinus Prastowo selaku Direktur Eksekutif menemukan kelebihan dan kekurangan dari rencana kebijakan pajak keuntungan modal (capital gain tax/ CGT) dan pajak final progresif (PFP) atas transaksi jual beli tanah tersebut.
Yustinus mengungkapkan, CGT adalah pajak atas keuntungan yaitu selisih antara harga jual dan harga perolehan atau harga beli.
“Misalnya tanah harga perolehan Rp100 juta, dijual Rp500 juta. Berarti ada selisih Rp400 juta. Ini yang dipajaki, misalnya 5 persen. Berarti pajaknya 5 persen x Rp400 juta jadi Rp20 juta,” kata Yustinus, Jumat (2/2).
Menurutnya, CGT memiliki kelebihan yaitu merupakan jenis pajak yang ideal, karena dikenakan atas keuntungan sehingga lebih adil dan sesuai prinsip pajak yang mana dikenakan atas tambahan kemampuan ekonomis.
Sementara, kelemahan CGT adalah minimnya ketersediaan basis data, yaitu data harga perolehan tanah dan data kepemilikan. Dua data tersebut hanya dimiliki oleh penjual dan pembeli tanah.
“Siapa sasarannya dan berapa nilai asetnya. Maka perlu integrasi data kepemilikan dan data nilai tanah yang baik, sinergi antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP),” ujarnya.
Sementara, PFP merupakan pengembangan dari pajak penghasilan (PPh) atas Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan yang dikenakan atas nilai pengalihan (nilai transaksi).
Progresif dikenakan karena sasarannya tanah yang menganggur atau kepemilikan kedua, ketiga, dan seterusnya. Dari contoh di atas, misalnya besaran pajak Rp25 juta yang berasal dari tarif 5 persen dikalikan nilai transaksi Rp500 juta.
“PFP bisa dianalogikan dengan kendaraan, saat kita memiliki kendaraan lebih dari satu, kendaraan kedua, ketiga, maka dikenai tarif progresif. PFP adalah modifikasi dari pajak final yang sudah ada, tinggal diubah tarif progresif untuk tanah menganggur atau kepemilikan kedua, ketiga, dan seterusnya,” jelasnya.
Kelemahan PFP, lanjut Yustinus, tidak ideal seperti CGT karena basisnya transaksi sehingga orang cenderung menghindari nilai pasar. Tantangan yang harus dijawab pemerintah adalah penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang kontinu sehingga mendekati harga pasar.
Atas dua konsep pungutan pajak tersebut, Yustinus menemukan lagi persamaan kelemahan dalam implementasinya, yaitu:
Pertama, dikenakan saat adanya transaksi. Padahal skema disinsentif ini justru akan efektif saat dikenakan tahunan (periodik) sehingga mendorong pemilik untuk mengusahakan lahan menjadi produktif, atau menjualnya.
“Kedua, selama ini ada Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk pembeli. Karena BPHTB ini domain Pemerintah Daerah (Pemda), maka sulit mengikuti perubahan kebijakan Pusat. Perlu adanya koordinasi,” jelasnya.
Melihat kelemahan kedua jenis pajak di atas, Yustinus mengusulkan adanya pajak yang dikenakan periodik (tiap tahun) dengan tarif progresif (seperti atas kendaraan), agar menjadi insentif orang untuk mengusahakan lahannya atau menjualnya.
Untuk itu, Pajak Bumi Bangunan (PBB) jadi pilihan yang memungkinkan.
Namun, perubahan harus melalui Undang-undang dan ada koordinasi pengaturan agar adil. Selain itu pemerintah pusat juga harus mengatasi masalah inkompatibilitas otonomi daerah dalam hal ini PBB Pedesaan Perkotaan adalah domain Pemda.
“Dengan demikian cukup jelas, ide yang baik ini perlu didukung namun juga perlu dipikirkan efektivitas implementasinya,” katanya.
Yustinus tidak ingin muncul ketidakadilan baru berupa BPHTB yang tetap tinggi di setiap daerah yang menerapkan perlakuan berbeda.
“Jangan sampai juga menciptakan loopholes untuk melakukan penghindaran pajak,” tegas Yustinus.
Ia juga menyarankan agar pemerintah segera memberikan penjelasan yang utuh dan menyeluruh, agar tujuan kebijakan ini tidak menimbulkan keresahan di kalangan pelaku usaha. Khususnya pengusaha real estate, atau kelompok masyarakat lainnya.
“Bahwa sasaran dan tujuan kebijakan ini cukup jelas dan tidak akan menimbulkan distorsi, bahkan menangkal upaya spekulasi dan melindungi akses warga negara pada tempat tinggal yang merupakan hak dasar, termasuk mendapatkan sumber daya berupa pajak untuk belanja sosial,” jelasnya.
Menurut Yustinus, saat ini merupakan momentum terbaik untuk memikirkan kebutuhan reformasi pajak menyeluruh dan komprehensif. Revisi UU Perpajakan sebaiknya disinkronkan dengan revisi UU terkait, termasuk UU Pertanahan. Hal ini pada akhirnya akan menciptakan sistem pajak yang berkeadilan.