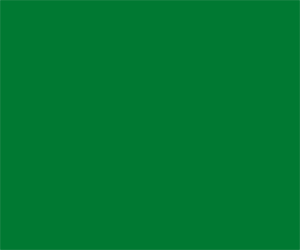Mungkin ini terdengar klise. Tapi adagium ‘menang dan kalah dalam politik adalah biasa’ merupakan sebuah konsepsi yang cukup rumit untuk dijalankan. Sebab sejatinya menang dan kalah dalam kontestasi politik bukanlah sebuah proses sekali jadi kemudian selesai begitu saja. Lebih dari itu, menang dan kalah sejatinya adalah sebuah proses yang terus berlangsung tanpa jeda.
Rumitnya, proses menang dan kalah memuat banyak efek yang menyertainya. Khusus dalam tulisan ini, saya akan mengaitkannya dengan hasil menang dan kalah di Pilkada DKI. Kita semua sama-sama sudah mengetahui hasil Pemilukada DKI yang mana pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno mampu memenangkan kontestasi. Hasil versi quick count pun cukup signifikan.
Sejumlah lembaga survei menempatkan kemenangan Anies-Sandi di kisaran 57 hingga 58 persen. Sebuah angka yang cukup fantastis. Ini adalah angka elektabilitas tertinggi sepanjang sejarah Pilkada di DKI. Pada Pilkada 2007 Fauzi Bowo (Foke) memang unggul sekitar 57 persen. Tapi jumlah partisipasi pemilihnya jauh lebih rendah jika dibandingkan Pilkada 2017. Sedangkan Jokowi hanya menang 52-an persen saat Pilkada 2012
Jadi bisa dibilang legitimasi kemenangan Anies-Sandi sangat kuat. Pilkada DKI juga menyajikan fakta bahwa belum pernah ada sekalipun pejawat yang sukses di ibu kota. Ini menjadi catatan kritis tersendiri. Tapi khusus untuk Ahok, situasinya berbeda. Sebab dia bukanlah gubernur pejawat yang terpilih via pemilihan umum. Sebaliknya, dia hanya seorang gubernur pengganti dari Jokowi.
Dengan kenyataan ini, sosok Jokowi secara tak langsung masih ada sangkut pautnya dengan Pilkada kali ini. Sebab hampir semua pemilih Ahok adalah pendukung Jokowi pada Pilkada 2012 dan Pilpres 2014 lalu.
Ahok seakan mewakili Jokowi dalam scope yang lebih mini. Saya lebih mengartikannya, Pilkada DKI menjadi pemilu sela bagi pemerintahan Jokowi dengan Ahok yang jadi representasinya. Memang, tak semua pendukung Jokowi suka dengan Ahok. Tapi bisa dipastikan pendukung Ahok mayoritas adalah pendukung Jokowi.
Sebaliknya, pendukung Prabowo pada 2014 lalu hampir semua mendukung Anies. Menariknya, ada beberapa pendukung Jokowi yang kini menyebrang memilih pasangan yang diusung Gerindra dan PKS itu.
Kalau mengacu pada hasil Pilpres 2014 dan Pilkada 2012, sejatinya suara Jokowi nyaris mirip, yakni 53 persenan. Sedangkan basis pendukung Prabowo dan Foke yang keduanya adalah rival Jokowi (pada 2014 dan 2012) adalah sekitar 46 persen.
Jika bertolak pada angka ini sebagai basis, maka kita bisa mengartikannya ada 46 persen rakyat yang berada di kubu oposisi Jokowi. Sebaliknya ada modal politik 53 persenan bagi kekuatan Jokowi di ibu kota.
Namun, hal ini tidak tersalurkan secara baik kepada Ahok. Mengapa hal ini terjadi? Apakah ada titik pergeseran dukungan politik secara umum antara pendukung Jokowi dan oposisi?
Secara moral bisa dibilang ya. Bisa dibilang Jokowi kalah di Pilkada DKI, sedangkan Prabowo menjadi pemenangnya.
Sebab selain citra Ahok yang begitu melekat dengan Jokowi, pengusung pasangan nomor dua ini semuanya adalah kekuatan politik pemerintah. Alasan PPP kubu Romi merapat ke Ahok pun membuktikan ada konsolidasi dari kekuatan pro Jokowi. Mendukung Ahok dianggap jadi pertaruhan kesolidan kekuatan politik pendukung pemerintah.
Dan ternyata, koalisi pemerintah gagal mempertahankan Ibu Kota. Sebaliknya oposisi mampu merebut pos politik strategis. Ini menjadi sebuah kemenangan sela yang vital jelang pertarungan sesungguhnya di 2019.
Sejatinya, jika ditengok secara umum, kekuatan pemerintah rontok hampir di pos-pos vital pada Pilkada serentak 2017. Sebelum kalah di DKI, kekuatan pro Jokowi sudah rontok di Banten dengan tumbangnya Rano Karno dari Wahidin Halim.
Walhasil ini jadi alarm bahaya bagi Jokowi menjelang 2019. Pertaruhannya akan makin besar, sebab pada 2018 nanti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur juga akan menghelat pemilihan.
Jika kembali kalah dalam salah satu di antara ketiga, maka posisi politik pemerintah akan semakin lemah. Koalisi yang dibangun pun akan semakin rentan. Dan yang terpenting, tingkat loyalitas sejumlah kekuatan yang selama ini begitu loyal pada pemerintah akan mulai memudar.
Mereka akan mulai membaca kemungkinan perubahan kekuasaan. Jika itu yang terjadi, akan banyak kekuatan dan aparat yang mulai mengamankan posisinya.
Tesis ini sangat mungkin terjadi jika kita berkaca statement SBY jelang roda kekuasaannya berakhir pada 2014. Saat itu SBY menyebut ada beberapa aparat yang mulai ‘lompat perahu’.
Lantas ada apa di balik tumbangnya pamor kekuatan pro pemerintah di sejumlah daerah? Apakah ada kaitannya dengan Ahok?
Memang butuh analisis mendalam untuk menjawabnya. Tapi jika mengacu pada hasil riset sejumlah lembaga atas hasil di Banten dan Jakarta, faktor Ahok ternyata memberi efek yang tidak main-main. Lebih tepatnya kasus Al-Maidah ayat 51 punya dampak yang tidak kecil bagi kekuatan pro pemerintah di sejumlah Pilkada.
Terkait hal ini mari kita mengkajinya secara mendalam dengan membuka fakta sejarah. Seperti disinggung di awal, proses kontestasi politik bukan proses sekali jadi. Ini adalah proses yang terus berlangsung sejak negara ini berdiri
Siklus menang dan kalah pun berputar-putar dalam pemilu. Tapi basis ideologi politik masyaralat sejatinya tak banyak mengalami perubahan. Sadar atau tidak, polarisasi politik yang terbentuk saat ini sejatinya tak banyak berubah dari 1955. Basis kekuatan politik hijau masih tetap di pesisir Sumatra, Jawa Barat, dan DKI.
Kekuatan ‘merah’ tetap bercokol di Jawa Tengah, Bali, dan sebagian luar Jawa. Dan Jawa Timur tetap menjadi poros kekuatan NU.
Polarisasi politik lawas itu tetap kekal. Sebab sejatinya, sadar atau tidak ideologi politik di Indonesia juga kerap diwariskan secara turun-temurun. Walau tak sesaklek agama, pilihan politik anak Indonesia umumnya sama dengan pilihan politik ayah, kakek, atau buyutnya.
Memang situasi ini tak berlaku 100 persen. Namun bisa dikatakan mayoritas pilihan ideologi politik Anda tak jauh berbeda dari ayah atau leluhur Anda. Nah, dengan polarisasi yang terbentuk sejak 1955 itu sejatinya mengukur langkah politik juga mesti menggunakan pena sejarah.
Dalam Pilkada 2017, polarisasi ini makin padat akibat munculnya kasus Al-Maidah. Kekuatan politik hijau yang sebelumnya masih ada yang bersimpati pada Jokowi (pada 2012 dan 2014), kini terpisah dari gerbongnya.
Mereka menuju gerbong sejarah lama yakni mendukung kekuatan politik hijau. Sebelum kasus Al Maidah bisa dikatakan posisi Jokowi di kalangan Islam tak terlalu berjarak secara ekstrem.
Pada 2012 masih ada sejumlah ulama atau tokoh Islam DKI yang membackup Jokowi. Meski status Ahok saat itu juga membuat sebagian kekuatan hijau lain mengambil jarak, tapi sifatnya masih cair. Ini karena sosok Jokowi yang saat itu begitu kuat secara individu sebagai eks wali kota Solo, bukan sosok politikus atau petugas partai yang berjarak dengan Islam.
Pun halnya pada Pilpres 2014. Meski terbit Obor Rakyat yang sempat membuat ada sedikit jarak antara Jokowi dan Islam, namun hal ini bisa ternetralisir dengan sosok Jusuf Kalla yang lekat dengan Islam. Saat itu pun secara pribadi belum ada jarak antara Jokowi dengan simbol Islam, seperti ulama.
Tapi sejak kasus Al-Maidah, semua polarisasi yang cair ini berubah menjadi padat. Ini juga tak terlepas kebijakan pemerintah menangkap sejumlah ulama dan memproses hukumnya.
Sejak itulah, Jokowi dan rezimnya mulai berjarak dengan Islam. Sejumlah konspesi baru yang membawa nama Islam pun coba dikembangkan pemerintah untuk menetralisir jarak tersebut. Tapi hal ini tak ternah efektif. Ini mirip dengan situasi politik pada akhir era Orde Baru yang coba membawa konsepsi baru dengan mencairkan Islam dengan nasionalis dan komunis.
Tapi secara praktik, ulama yang berseberangan dengan pemerintah kala itu pun juga dibui. Fakta itu yang membuat rezim Orde Lama begitu berjarak dengan Islam.
Kembali ke kasus Pilkada DKI, kekuatan politik hijau akhirnya semakin padat terkonsolidasi. Usaha mencitrakan Islam radikal kepada kalangan hijau yang anti Ahok pun gagal total.
Sebab memang sejatunya, kekuatan hijau di DKI memang bukanlah kalangan Islam ekstrim. Sebab kekuatan hijau di DKI sejatinya di dominasi NU. Namun NU di DKI tak bisa dikendalikan secara struktural namun kultural. Yang punya kendali adalah kiai, ulama, dan habaib.
Saat sejumlah kiai, ulama, dan habaib justru mendapat represi dari kekuatan kekuasaan, hal itulah yang jadi bumerang. Dan akibatnya, kini kekuatan pro Jokowi kalah total di Jakarta. Efek dari Al Maidah ternyata tak hanya di DKI tapi merambah hingga daerah lain.
Ini terbukti dengan kekalahan sejumlah koalisi yang digalang PDIP di sejumlah provinsi dan kota. Sentimen Al Maidah diprediksi akan terus bergulir di Jawa Barat dan sejumlah daerah yang akan menggelar Pilkada 2018.
Walhasil, ini menjadi catatan minus bagi seorang Ridwan Kamil yang kini memilih meninggalkan perahu Gerindra dan PKS menuju Nasdem. Sebab di sisi lain, Nasdem citranya begitu lekat sebagai pendukung Ahok. Sekalipun dalam sejumlah kesempatan sejumlah pihak mengatakan polarisasi di daerah berbeda dengan DKI, tapi fakta di Banten menunjukkan sebaliknya.
Jika Ridwan Kamil diusung kekuatan politik yang sama dengan partai pengusung Ahok, maka sentimen efek kasus Al Maidah terancam menghantamnya. Sinyal ke arah itu sudah mulai terlihat kini. Ridwan Kamil mulai kehilangan kepercayaan dari kalangan Islam. Sinyal ini terlihat secara kasat mata dalam perbincangan di lini massa.
Dengan kenyataan di DKI, bukan tak mungkin seorang Ridwan Kamil akan kembali mengatur ulang langkahnya. Sebab meninggalkan Gerindra demi Nasdem demi tiket Pilkada Jabar adalah sebuah blunder politik besar yang sulit dicerna dengan akal sehat. Apalagi kini melihat hasil di DKI.
Walhasil, butuh usaha ekstra dari Ridwan Kamil untuk mentralisir ancaman sentimen dari pemilih islam yang terpengaruh kasus Al Maidah. Bukan hanya di Jawa Barat, sentimen ini juga bisa saja merambah ke Pilpres 2019. Tentu Jokowi cukup cerdas membaca fenomena ini. Sehingga usaha merangkul ulama terus dilakukannya. Ini terlihat dengan langkah Jokowi mengumpulkan sejumlah ulama, beberapa waktu lalu.
Langkah Jokowi untuk merapatkan kembali jaraknya dengan Islam juga bisa terlihat dalam penuntasan kasus al-Maidah yang menjerat Ahok. Tentunya penuntasan kasus ini akan membuat sentimen al-Maidah berhenti. Sebab penegakan hukum yang adil telah dilaksanakan.
Namun jika sebaliknya, sentimen al-Maidah malah akan menjadi kartu truf lawan politik Jokowi. Kartu yang bisa jadi menghambat langkahnya di 2019.
Terkait 2019 ini pun Jokowi harus berhati-hati dalam memilih siapa partner dan gerbong politiknya. Memilih calon wapres yang awalnya begitu sederhana kini menjadi lebih sulit jika melihat hasil Pilkada DKI.
Wapres yang bisa menjembatani Jokowi dengan Islam kini menjadi kebutuhan. Dengan begitu, Jokowi bisa kembali mempertahankan suara Islam yang sejatinya jadi kunci kemenangannya atas Prabowo di 2019. Ingat, isu yang disebut memenangkan Jokowi di detik akhir Pilpres adalah terkait Islam, yakni kontroversi hari santri.
Apa pun itu Pilkada DKI ini membawa titik balik secara politik. Langkah yang telah disusun kini jadi dipikirkan ulang. Sebab salah melangkah peluang terancam melayang.
Maka bukan hal yang aneh jika Pilakda DKI akan membawa arah politik baru. Loyalitas dan legitimasi terhadap penguasa mendapat ujian. Akan banyak politisi dan aparat yang mulai melirik kekuatan oposisi yang terus meraih kemenangan di sejumlah Pilkada.
Sebaliknya, rezim penguasa bisa jadi merubah strategi dan pendekatan politiknya. Polarisasi politik baru menjadi hal yang niscaya. Bukan hal yang tak mungkin akan ada kocok ulang siapa kawan dan lawan.